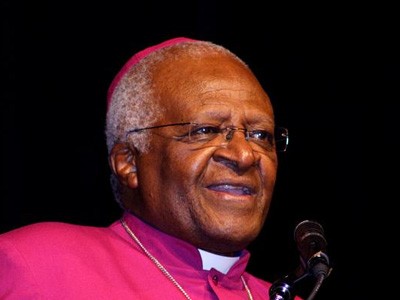Konferensi Pikiran dan Kehidupan VIII: Emosi yang merusak
Dihadiri oleh HH Dalai Lama, di Dharamsala, India

Dimulai pada pertengahan 1980-an, Mind and Life Institute telah mempertemukan para ilmuwan dari berbagai bidang keahlian dengan His Holiness the Dalai Lama dalam serangkaian konferensi. Tema dipilih untuk masing-masing, dan lima hingga tujuh ilmuwan di bidang itu dipilih untuk memberikan presentasi kepada Yang Mulia. Presentasi ini diberikan di sesi pagi setiap hari, dan diskusi yang hidup di antara para peserta kunci ini, yang duduk melingkar, mengisi sesi sore. Selain para ilmuwan, hadir juga dua penerjemah bahasa Tibet-Inggris. Sekelompok pengamat—berjumlah 20 sampai 40—duduk di pinggiran. Suasananya informal dan intim. Topik konferensi sebelumnya berkisar dari fisika dan astronomi hingga tidur dan mimpi hingga hubungan antara pikiran dan otak.
Kedelapan Konferensi Pikiran dan Kehidupan, diadakan di Dharamsala 20-24 Maret 2000, membahas topik tentang emosi yang merusak. Meskipun tidak mungkin untuk meringkas proses yang rumit dengan cara yang menyenangkan bagi semua orang, saya akan menyebutkan beberapa hal penting serta membahas beberapa poin yang menurut saya paling menarik.
Kecenderungan moral
Dr Owen Flanagan, Profesor Filsafat di Universitas Duke, berbicara tentang peran emosi dan kebajikan dalam membuat kehidupan yang baik. Barat memiliki beberapa pendekatan untuk ini. Filsafat moral agama berbicara tentang sifat destruktif dari beberapa emosi dan peningkatan kualitas manusia melalui praktik keagamaan, sedangkan filsafat moral sekuler membahas topik tersebut dalam kerangka demokrasi dan nalar. Sains melihat emosi memiliki dasar fisiologis, dan ini menimbulkan pertanyaan lebih lanjut tentang sifat manusia dan kemungkinan menenangkan emosi yang merusak. Di Barat, emosi penting untuk menentukan apa itu moral, dan moralitas sangat penting untuk berfungsinya masyarakat. Jadi bekerja dengan emosi dipandang penting untuk interaksi sosial, bukan untuk memiliki jiwa yang baik atau menjadi orang yang baik. Hal ini membuat Barat berfokus pada harga diri dan pencapaian diri sebagai emosi positif, bukan pada kehidupan emosional batin yang harmonis.
Kami menemukan tiga jawaban utama sebagai jawaban atas pertanyaan, "Seperti apa sebenarnya kita jauh di lubuk hati?" Egois rasional mengatakan bahwa kita mencari kebaikan kita sendiri, dan tahu bahwa hanya dengan bersikap baik kepada orang lain kita akan mendapatkan apa yang kita inginkan. Yang kedua adalah pertama-tama kita egois dan menjaga diri kita sendiri dan kemudian dengan penuh kasih berbagi sumber daya ekstra apa pun dengan orang lain. Yang ketiga adalah pada dasarnya kita berbelas kasih, tetapi jika ada kelangkaan sumber daya, kita menjadi egois. Yang Mulia percaya bahwa manusia pada dasarnya lembut dan penyayang, dan karena itu keegoisan dan ketidaktahuan, kita merasa dan bertindak dengan cara yang berlawanan. Namun, kita tidak dapat mengatakan bahwa sifat manusia biasa adalah menghargai orang lain.
Budaya Barat menganggap cinta dan kasih sayang berorientasi pada orang lain. Yang Mulia mengklarifikasi bahwa dalam Buddhisme, mereka juga dirasakan terhadap diri sendiri. Menginginkan diri kita bahagia dan bebas dari penderitaan belum tentu egois. Memiliki perasaan itu dengan cara yang sehat adalah penting untuk mempraktikkan sang jalan, dan itu tercakup dalam cinta dan welas asih yang kita kembangkan di jalan tersebut.
Kondisi mental
Ven. Mattieu Ricard, seorang ilmuwan dan penganut Buddha biarawan, memberikan ringkasan yang sangat bagus tentang pendekatan Buddhis terhadap pikiran, berbicara tentang sifat pikiran yang murni bercahaya, distorsi dari emosi yang merusak, dan potensi untuk melenyapkannya.
Yang Mulia menyebutkan dua jenis emosi. Emosi pertama, impulsif, destruktif, didasarkan pada kesalahpahaman dan karenanya tidak dapat dikembangkan tanpa batas. Yang kedua, yang realistis, seperti welas asih dan kekecewaan terhadap samsara, dapat ditingkatkan tanpa batas. Yang pertama didasarkan pada alasan tidak logis yang dapat dibantah, sedangkan yang kedua didasarkan pada observasi dan penalaran yang valid. Kita harus menggunakan penalaran yang benar untuk mengembangkan kondisi mental yang berlawanan dengan emosi yang merusak. Misalnya cinta, sebagai penawar racun marah, harus dipupuk melalui penalaran. Itu tidak akan muncul hanya dengan berdoa kepada Budha. Dia juga menyarankan agar para ilmuwan melakukan studi neurologis untuk menentukan apakah kedua jenis emosi ini terkait dengan aktivitas otak tertentu.
Kesadaran konseptual
Dr. Paul Ekman, Profesor Psikologi di UCSF Medical School, berbicara tentang evolusi emosi manusia. Sebelumnya dianggap bahwa emosi, seperti bahasa dan nilai, berbeda dari satu budaya ke budaya lainnya. Namun, Darwin melihat mereka sebagai hal yang umum bagi semua orang dan juga ada pada hewan. Penelitian Ekman menunjukkan bahwa lintas budaya, semua orang mengidentifikasi ekspresi wajah tertentu yang menunjukkan emosi yang sama. Juga, perubahan fisiologis yang sama terjadi pada orang-orang dari semua budaya ketika mereka merasakan emosi tertentu. Misalnya, saat takut atau marah, detak jantung setiap orang meningkat. Emosi muncul dengan cepat. Kami merasa bahwa emosi terjadi pada kami, bukan karena kami memilihnya. Kami tidak menyaksikan proses yang mengarah ke mereka dan sering menyadari mereka hanya setelah mereka kuat. Di sini Yang Mulia memberikan contoh mengidentifikasi kelemahan dan kegembiraan dalam meditasi. Awalnya, kami tidak dapat mengidentifikasinya dengan cepat tetapi dengan pengembangan kewaspadaan, kami dapat mendeteksinya bahkan sebelum muncul.
Ekman membedakan antara pikiran yang bersifat pribadi dan emosi yang tidak bersifat pribadi. Misalnya, jika seseorang takut saat ditangkap, kita tahu emosinya, tetapi kita tidak tahu pikiran yang memicunya, yaitu apakah dia takut karena tertangkap atau karena dia tidak bersalah? Pikiran dan emosi itu berbeda. Yang Mulia menjawab bahwa dalam Buddhisme kata “namtog” (prakonsepsi atau takhayul) mencakup keduanya. Juga, keduanya adalah kesadaran konseptual, dan keduanya harus ditransformasikan di jalan.
Suasana hati dan manifestasi
Sementara emosi muncul dan berhenti relatif cepat, suasana hati bertahan lebih lama. Kami biasanya dapat mengidentifikasi peristiwa tertentu yang menyebabkan emosi, tetapi seringkali tidak bisa untuk suasana hati. Suasana hati membiaskan cara kita berpikir dan membuat kita rentan dengan cara yang biasanya tidak kita lakukan. Saat kita sedang bad mood, misalnya, kita mencari kesempatan untuk marah. Tidak ada kata dalam bahasa Tibet untuk "suasana hati", tetapi Yang Mulia berkata bahwa mungkin ketidakbahagiaan mental yang dikatakan Shantidewa adalah bahan bakar untuk marah bisa jadi contohnya.
Selain emosi dan suasana hati, ada sifat dan manifestasi patologis dari emosi. Misalnya, ketakutan adalah emosi, ketakutan adalah suasana hati, rasa malu adalah ciri pribadi, dan fobia adalah manifestasi patologis.
Setelah emosi destruktif muncul, ada periode refraktori di mana informasi baru tidak dapat memasuki pikiran kita dan kita hanya memikirkan hal-hal yang memperkuat emosi tersebut. Hanya setelah waktu ini kita dapat melihat situasi dengan lebih masuk akal dan tenang. Misalnya, jika seorang teman terlambat, kita mengira dia sengaja menghina kita dan menganggap semua yang dia lakukan setelah itu sebagai sikap bermusuhan. Terapi bertujuan untuk mempersingkat periode refraktori ini dan membantu orang tersebut mengendalikan perilakunya selama periode refraktori.
Ilmu saraf afektif
Richard Davidson, Profesor Psikologi dan Psikiatri di University of Wisconsin, berbicara tentang fisiologi emosi yang merusak, juga disebut ilmu saraf afektif. Mengeluarkan otak plastik merah muda cerah, dia menunjukkan kepada Yang Mulia berbagai area yang diaktifkan selama persepsi dan emosi tertentu. Aktivitas tertentu, seperti bermain tenis atau memiliki emosi, bersifat kompleks dan banyak area otak yang terlibat di dalamnya. Namun, pola tertentu dapat dilihat. Misalnya, seseorang dengan kerusakan pada lobus frontal bawah memiliki lebih banyak emosi yang tidak diatur, sedangkan lobus frontal kiri lebih aktif saat kita memiliki emosi positif. Baik pada depresi maupun gangguan stres pascatrauma, hippocampus menyusut. Amigdala adalah pusat emosi negatif, terutama ketakutan, dan amigdala menyusut pada seseorang dengan agresi yang tidak terkendali. Amigdala dan hippocampus berubah sebagai respons terhadap pengalaman kita dan dipengaruhi oleh lingkungan emosional tempat kita dibesarkan.
Semua bentuk idaman—kecanduan obat, perjudian patologis, dll.—melibatkan kelainan pada tingkat dopamin di otak. Perubahan molekuler dopamin yang terjadi selama idaman mengubah sistem dopamin, sehingga objek yang sebelumnya netral menjadi penting. Selain itu, sirkuit otak yang berbeda terlibat dalam keinginan dan kesukaan. Saat kita mendambakan sesuatu, sirkuit keinginan menjadi kuat dan sirkuit rasa suka melemah. Orang tersebut terus-menerus merasa tidak puas dan membutuhkan lebih banyak dan lebih baik. Richardson mengusulkan beberapa penangkal terhadap emosi negatif yang merusak: mengubah aktivitas otak, mengubah periode refraktori, melakukan restrukturisasi kognitif dengan belajar berpikir secara berbeda tentang peristiwa, dan mengembangkan emosi positif.
Budaya dan emosi
Jeanne Tsai, Asisten Profesor Psikologi di University of Minnesota, berbicara tentang budaya dan emosi. Budaya berbeda dalam pandangan mereka tentang diri, dan itu memengaruhi emosi orang. Dengan demikian, terapi yang berhasil pada orang Eropa-Amerika seringkali tidak berhasil untuk orang Asia-Amerika. Pada umumnya orang Barat merasa dirinya mandiri dan terpisah dari orang lain. Ketika diminta untuk menggambarkan diri mereka sendiri, orang Amerika berbicara tentang atribut internal mereka, dengan mengatakan, "Saya ramah, pintar, menarik, dll." Orang Asia, di sisi lain, mengalami diri mereka sebagai terhubung dengan orang lain dan didefinisikan dalam hubungan sosial. Mereka menggambarkan diri mereka sendiri dalam kaitannya dengan peran sosial mereka— “Saya seorang anak perempuan, pekerja di tempat ini, dll.” Orang dengan diri mandiri berusaha untuk membedakan diri dari orang lain. Mereka menekankan peningkatan diri, mengekspresikan keyakinan dan emosi mereka, dan memberi tahu orang lain tentang kualitas baik mereka sendiri. Mereka menghargai perbedaan dari orang lain dan menghargai konflik karena memberikan kesempatan untuk mengungkapkan perasaan dan pendapat mereka. Mereka fokus pada diri mereka sendiri selama interaksi dengan orang lain, dan menghargai emosi seperti harga diri dan harga diri. Orang-orang dengan diri yang saling bergantung berusaha untuk mempertahankan hubungan. Jadi mereka meminimalkan kepentingan mereka sendiri, rendah hati, dan mengontrol bagaimana mereka mengekspresikan keyakinan dan emosi mereka untuk menjaga keharmonisan dengan orang lain. Emosi mereka muncul lebih lambat dan mereka kembali ke garis dasar lebih cepat daripada orang Barat. Selama interaksi, mereka lebih fokus pada orang lain dan menghargai emosi seperti kerendahan hati dan kemauan untuk bekerja sama.
Sebagai seseorang yang telah mengajarkan agama Buddha dalam berbagai budaya, saya menemukan hal ini menarik. Itu membuat saya bertanya-tanya: Apakah aspek-aspek berbeda dari Dharma perlu ditekankan sesuai dengan kesadaran diri yang ditemukan dalam suatu budaya? Selain itu, Buddhisme telah diekspresikan dari generasi ke generasi dalam budaya dengan kesadaran diri yang saling bergantung. Lalu, apa yang akan berubah dan apa yang harus kita waspadai agar tidak berubah saat agama Buddha menyebar ke dalam budaya di mana diri yang mandiri dihargai?
Pendidikan emosional
Mark Greenberg, Profesor Pembangunan Manusia dan Studi Keluarga di Pennsylvania State University berbicara tentang pendidikan emosional. Setelah mempelajari perkembangan emosi, dia mengembangkan sebuah program yang mengajarkan anak-anak kecil bagaimana mengelola emosi destruktif mereka, khususnya marah. Ini membantu anak-anak untuk menenangkan diri (yaitu mengurangi periode refraktori), menyadari keadaan emosional dalam diri mereka dan orang lain, mendiskusikan perasaan mereka sebagai metode untuk memecahkan masalah, merencanakan ke depan untuk menghindari kesulitan, dan menyadari efek perilaku mereka terhadap orang lain. . Mereka mengajari orang lain bahwa emosi adalah sinyal penting tentang kebutuhan mereka sendiri dan orang lain, bahwa perasaan itu normal tetapi perilakunya mungkin sesuai atau tidak, bahwa mereka tidak dapat berpikir jernih sampai mereka tenang, dan memperlakukan orang lain dengan cara mereka. ingin diperlakukan. Program ini berisi pelajaran tentang berbagai emosi dan kebalikannya. Anak-anak juga memiliki satu set kartu dengan ekspresi wajah emosi yang berbeda yang dapat mereka perlihatkan sehingga orang lain tahu bagaimana perasaan mereka.
Yang Mulia senang dengan hal ini dan menambahkan bahwa selain mengelola emosi yang merusak, anak-anak (dan orang dewasa juga) perlu memupuk emosi positif juga. Meskipun emosi positif ini mungkin tidak dapat digunakan di saat panas, emosi ini memengaruhi temperamen kita dan menjadi fondasi yang baik, seperti memperkuat "sistem kekebalan" emosional kita. Davidson mengatakan bahwa ketika kita sering berlatih, otak kita juga berubah.
neuroplastisitas
Francisco Varela, Profesor Ilmu Kognitif dan Epistemologi di Ecole Polytechnique, berbicara tentang neuroplastisitas. Dia menjelaskan teknik baru yang lebih halus untuk mengukur menit atau perubahan singkat di otak, dan menunjukkan diagram komputer tentang sinkronisitas atau kekurangannya di antara area otak yang berbeda selama proses melihat dan mengetahui suatu objek. Yang Mulia mengatakan mungkin ada hubungan antara itu dan proses kesadaran visual kita dan kemudian kesadaran mental kita mengenali suatu objek. Dia menyarankan untuk mengajar lorig (pikiran dan fungsinya) dalam hubungannya dengan ilmu saraf untuk membuat topik lebih relevan.
Sedangkan Yang Mulia tertarik dengan diskusi tentang aktivitas otak, yang lain memiliki reaksi yang berbeda. Sains mengajarkan bahwa susunan genetik, lingkungan, dan pengalaman eksternal memengaruhi otak, yang pada gilirannya menciptakan emosi dan mengarah ke pikiran. Dari pandangan Buddhis, pikiran memengaruhi emosi, yang pada gilirannya memengaruhi perilaku dan fungsi otak. Beberapa orang menganggap pandangan ilmiah melemahkan karena dengan menekankan faktor-faktor eksternal, tampaknya hanya sedikit yang dapat dilakukan individu untuk memengaruhi emosi dan pikirannya. Mereka menganggap pandangan Buddhis lebih memberdayakan karena tampaknya kita dapat melakukan sesuatu untuk membantu diri kita sendiri.
Mendefinisikan emosi
Setelah meringkas peristiwa-peristiwa utama, saya ingin membahas beberapa poin yang menurut saya sangat menarik. Pertama, tidak ada kata untuk “emosi” dalam bahasa Tibet. Klesa (sering diterjemahkan sebagai delusi, kesengsaraan, atau sikap gelisah dan emosi negatif) mencakup sikap serta emosi. Ketika para ilmuwan diberikan daftar enam akar dan dua puluh klesa sekunder dari teks lorig dan diberi tahu bahwa gambaran Buddhis tentang emosi yang merusak, mereka tidak mengerti mengapa ketidaktahuan, misalnya, disebut emosi. Juga tidak jelas bagi mereka mengapa sikap seperti itu salah 'view' disiplin etika, dan emosi seperti kecemburuan, digabungkan dalam satu daftar. Belakangan mereka mengetahui bahwa ini termasuk dalam satu daftar karena mereka semua menyebabkan samsara dan menghalangi pembebasan.
Kedua, makna emosi menurut sains dan agama Buddha berbeda. Dari sudut pandang ilmiah, emosi memiliki tiga aspek: fisiologis, perasaan, dan perilaku. Aktivitas otak dan perubahan hormonal adalah fisiologis, dan tindakan agresif atau pasif adalah perilaku. Dalam Buddhisme, emosi mengacu pada kondisi mental. Sedikit yang dikatakan tentang perubahan fisiologis, mungkin karena instrumen ilmiah untuk mengukurnya tidak tersedia di India kuno atau Tibet. Buddhisme juga membedakan antara emosi marah dan tindakan fisik atau verbal untuk bersikap asertif, yang mungkin atau mungkin tidak dimotivasi oleh marah. Demikian pula, seseorang mungkin sabar di dalam, tetapi memiliki perilaku asertif atau pasif, tergantung pada situasinya.
Ketiga, umat Buddha dan ilmuwan berbeda pendapat tentang apa yang dianggap sebagai emosi yang merusak. Misalnya, para ilmuwan mengatakan bahwa kesedihan, rasa jijik, dan ketakutan adalah emosi negatif dalam artian tidak menyenangkan untuk dialami. Namun, dari sudut pandang Buddhisme, dibahas dua jenis kesedihan, rasa jijik, dan rasa takut. Salah satunya didasarkan pada distorsi, mengganggu pembebasan, dan harus ditinggalkan, misalnya, kesedihan karena putusnya hubungan romantis dan ketakutan kehilangan pekerjaan. Jenis kesedihan lainnya membantu kita di jalan. Sebagai contoh, ketika prospek mengalami kelahiran kembali satu demi satu dalam samsara membuat kita sedih dan bahkan memenuhi kita dengan rasa jijik dan ketakutan, hal itu positif karena mendorong kita untuk membangkitkan tekad untuk bebas dari samsara dan mencapai pembebasan. Kesedihan, kejijikan, dan ketakutan seperti itu adalah positif karena didasarkan pada kebijaksanaan dan mendorong kita untuk berlatih dan mencapai realisasi sang jalan.
Mengalami emosi
Sains mengatakan semua emosi itu alami dan baik-baik saja, dan bahwa emosi menjadi destruktif hanya ketika diungkapkan dengan cara atau waktu yang tidak tepat atau kepada orang atau tingkat yang tidak pantas. Misalnya, mengalami kesedihan ketika seseorang meninggal adalah hal yang wajar, tetapi orang yang depresi merasa sedih dalam situasi yang tidak pantas atau pada tingkat yang tidak pantas. Tampilan emosi fisik dan verbal yang tidak tepat perlu diubah, tetapi reaksi emosional, seperti marah, tidak buruk dalam diri mereka sendiri. Terapi lebih ditujukan untuk mengubah ekspresi eksternal dari emosi daripada pengalaman internalnya. Buddhisme, di sisi lain, percaya bahwa emosi yang merusak itu sendiri adalah rintangan dan perlu dihilangkan untuk mendapatkan kebahagiaan.
Pertanyaan “Apakah ada bentuk positif dari marah?” muncul beberapa kali. Beberapa ilmuwan percaya bahwa dari sudut pandang biologi evolusioner, marah memungkinkan manusia untuk menghancurkan musuh mereka, dan dengan demikian tetap hidup dan bereproduksi. Tipe lain dikaitkan dengan dorongan konstruktif untuk menghilangkan hambatan. Misalnya, jika seorang anak tidak dapat meraih mainannya, mainannya marah membuatnya berpikir bagaimana mendapatkannya. Yang Mulia berkomentar bahwa ini marah dapat digabungkan dengan pemecahan masalah, tetapi tidak selalu membantu untuk memecahkan masalah. Itu disebut "positif" berdasarkan efeknya — orang mendapatkan apa yang diinginkannya — bukan karena bajik. Selain itu, seperti marah tidak selalu mengarah pada pemecahan masalah. Misalnya, frustrasi dan marah karena ketidakmampuan kita untuk berkonsentrasi ketika bermeditasi, alih-alih membantu kita mencapai kediaman yang tenang, halangi latihan kita. Yang Mulia tidak setuju bahwa ada bentuk positif dari marah. Meskipun secara sekuler, marah pada seseorang yang merugikan dirinya sendiri atau orang lain bisa disebut "positif", arhat bebas dari ini. Jadi, benar marah adalah kekotoran batin yang harus dihilangkan untuk mencapai nirwana. Kita dapat berbelas kasih kepada orang tersebut dan tetap berusaha menghentikan perilakunya yang berbahaya. Jadi, sementara Barat menilai kemarahan moral sebagai emosi, dari sudut pandang Buddhis, memang demikian terampil berarti, perilaku yang dimotivasi oleh kasih sayang.
Para Buddha merasakan emosi
Dalam Konferensi Pikiran/Kehidupan sebelumnya, muncul pertanyaan: Apakah a Budha punya emosi? Setelah banyak diskusi, diputuskan bahwa para Buddha memang memiliki emosi, misalnya, cinta dan welas asih yang tidak memihak untuk semua makhluk. Mereka merasa murah hati dan sabar. Mereka peduli dengan orang lain dan merasa sedih saat melihat orang lain menderita. Namun, a BudhaKesedihan melihat penderitaan berbeda dengan perasaan kebanyakan orang. Kesedihan kita adalah bentuk kesusahan pribadi; kita merasa putus asa atau depresi. Para Buddha, di sisi lain, sedih karena orang lain tidak mengamati karma dan efeknya dan dengan demikian menciptakan penyebab penderitaan mereka sendiri. Para Buddha merasakan harapan dan optimisme akan masa depan karena mereka tahu bahwa penderitaan seperti itu dapat berakhir karena sebab-sebabnya—sikap gelisah, emosi negatif, dan karma—dapat dihilangkan. Buddha juga jauh lebih sabar daripada kita. Mengetahui bahwa menghentikan penderitaan bukanlah perbaikan cepat, mereka senang bekerja lama untuk mengatasinya.
Yang Mulia Thubten Chodron
Venerable Chodron menekankan penerapan praktis dari ajaran Buddha dalam kehidupan kita sehari-hari dan khususnya ahli dalam menjelaskannya dengan cara yang mudah dipahami dan dipraktikkan oleh orang Barat. Dia terkenal karena ajarannya yang hangat, lucu, dan jelas. Ia ditahbiskan sebagai biksuni Buddhis pada tahun 1977 oleh Kyabje Ling Rinpoche di Dharamsala, India, dan pada tahun 1986 ia menerima penahbisan bhikshuni (penuh) di Taiwan. Baca biodata lengkapnya.